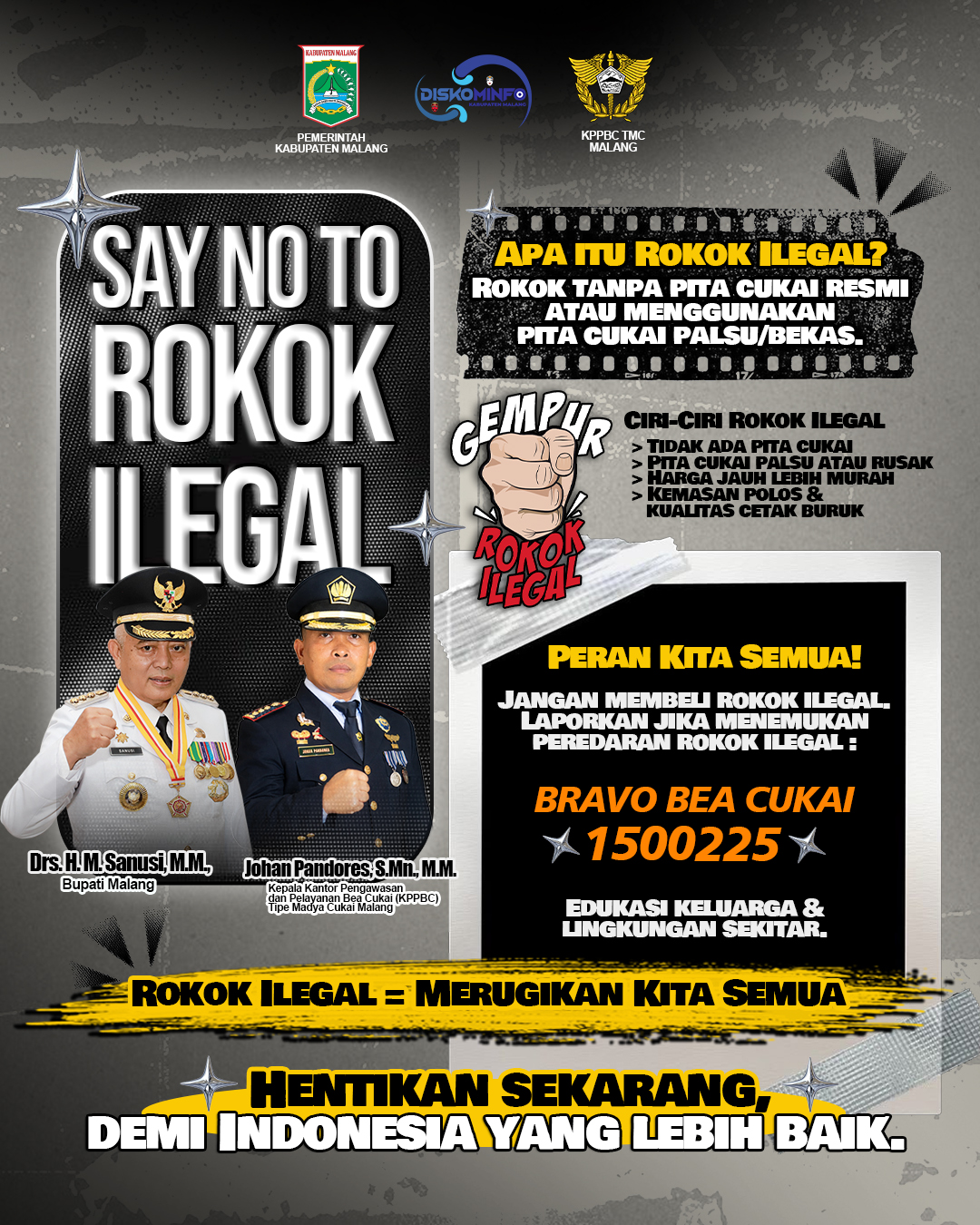Sudutkota.id – Kedungkandang, adalah nama sebuah Kecamatan di Kota Malang. Namun, bila melintasi wilayah timur Kota Malang ini, barangkali tak akan pernah anda duga, jika tanah yang anda pijak menyimpan luka yang belum betul-betul sembuh.
Melalui jalan-jalan menuju Rolak, menyeberangi jembatan tua di atas Sungai Amprong, atau melangkah ke arah perkampungan warga, sebuah cerita melatarbelakangi penamaan tersebut.
Kedungkandang, nama itu mungkin terdengar biasa. Bahkan bagi sebagian orang, barangkali hanya sebatas nama kelurahan administratif, hasil dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 140-150 tanggal 22 November 1980 dan No: 140-135 tanggal 14 Februari 1981 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
Namun bagi sebagian warga tua di wilayah itu, Kedungkandang bukan sekadar nama. Ia adalah penanda tragedi. Ia adalah pusaka cerita yang tak tertulis dalam buku sejarah. Ia hidup dalam bisik-bisik menjelang magrib, dalam sisa gamelan yang sesekali terdengar dari balik kabut malam.
Mula-Mula, Ada Dua Dukuh dan Dua Sungai
Dahulu, jauh sebelum ada jalan aspal, bangunan beton, dan jaringan listrik, kawasan ini terdiri atas dua dukuh tua, Dukuh Amprong dan Dukuh Bango. Masing-masing dinamai berdasarkan sungai yang mengalir di tengahnya, Sungai Amprong dan Sungai Bango. Dua aliran air yang menjadi sumber kehidupan sekaligus saksi bisu perubahan zaman.
Menurut cerita turun-temurun, masyarakat kala itu hidup rukun, damai, dan agamis. Gotong royong masih kuat, tanahnya subur, dan kesadaran spiritual tumbuh di antara keyakinan pada Tuhan dan penghormatan pada alam. Namun di balik itu, peradaban masih sangat sederhana. Masyarakat masih percaya benda-benda keramat. Batu besar, pohon beringin, atau sumur tua yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
Keyakinan pada hal mistis dari yang bersifat kepercayaan hingga tahayul, bukan hal aneh. Sebab hidup kala itu sulit. Apalagi di wilayah selatan dukuh, tanah-tanah terbentang luas namun kering dan tandus. Air sangat langka, bahkan untuk mandi atau minum pun warga harus menempuh perjalanan jauh.
Kekeringan adalah musuh lama. Dan dalam keyakinan lokal, ketika akal tak lagi mampu menjawab kesulitan, maka supranatural pun dijadikan jalan.
Proyek Belanda yang Berujung Tumbal
Sekitar tahun 1943, di tengah masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial memutuskan membangun bendungan besar di Sungai Amprong, kawasan Rolak Kedungkandang. Proyek ini dimaksudkan untuk mengairi lahan-lahan kering di Malang Selatan, mulai Gedangan hingga Bango.
Namun upaya itu selalu gagal. Bendungan roboh. Tanah ambles. Pekerja celaka. Mesin-mesin rusak tanpa sebab jelas.
Warga mulai berbisik, ada yang tidak berkenan. Sungai ini bukan sembarang sungai. Di dasar kedung, katanya, ada yang menunggu. Sesuatu yang tak kasat mata.
Dalam keputusasaan itu, seorang pertapa lokal melakukan semedi. Ia bertapa di tepian kedung, di antara gemericik air dan bayangan pohon bambu. Dan dalam sunyi malam, datanglah suara yang tidak berasal dari dunia ini.
“Hai cucuku, bila kamu ingin apa yang menjadi harapanmu berhasil, kamu harus berani berkorban… Di dalam kedung itu harus diberi tumbal seorang tandak.”
Suara itu datang dari sosok gaib berjubah putih, kata warga. Sang pertapa kaget dan gelisah. Namun suara itu muncul lagi, lebih keras, lebih memaksa.
“Satu jiwa perempuan tukang tayub harus dikorbankan. Bila tidak, bendungan akan selalu gagal. Semua harapan masyarakat akan sia-sia.”
Setelah selesai bertapa, sang pertapa memanggil para tokoh desa dan pemuka agama. Mereka bermusyawarah dalam pertemuan tertutup, mencoba menafsirkan pesan gaib itu. Akhirnya, dengan berat hati, permintaan itu disampaikan kepada pemerintah kolonial.
Dan, seperti mencampakkan etika kemanusiaan, pemerintah Belanda menyetujui. Bagi mereka, ini bagian dari “ritual lokal”, asal proyek berhasil.
Tandak-Tandak yang Tak Pernah Kembali
Tujuh malam tujuh hari, diadakanlah pertunjukan tayub besar-besaran di lokasi proyek. Para penari tandak, sinden, dan pengrawit didatangkan dari berbagai daerah. Tulungagung, Blitar, Kediri dan Wagir. Mereka datang dengan semangat, mengira akan menghibur para tamu dan pejabat.
Namun yang tak mereka tahu, mereka sedang menuju liang kematian.
Pada malam terakhir, saat gong ditabuh, gamelan mengalun cepat, dan tarian mencapai puncaknya, para tandak dibawa ke arah sumur besar yang telah disiapkan.
“Di sana, mereka ditodong senjata. Dipaksa masuk ke kedung bersama gamelan. Dan mereka tak pernah kembali,” ujar Dwi Wicaksono, sejarawan lokal.
Warga sekitar tak bisa berbuat banyak. Sebagian menunduk dan menangis dalam diam. Sebagian lainnya menutup sumur dengan batu dan tanah. Dalam tangis tertahan, mereka hanya bisa berdoa.
Dan setelah itu, keajaiban terjadi. Bendungan berhasil dibangun. Irigasi berjalan. Tanah-tanah tandus pun mulai mengalir air. Pemerintah kolonial berpesta merayakan “keberhasilan”.
Nama yang Menyimpan Arwah
Sebagai bentuk peringatan, tokoh agama lokal yang memimpin proses spiritual itu memberi nama tempat ini.
“Maka tercapailah apa yang menjadi idaman bersama. Tempat ini saya beri nama Kedung Gandang, kedung tempat dikuburnya seorang tandak yang sedang gandang. Tapi agar mudah disebut, maka kita singkat, Kedungkandang.”
Sejak itu, nama itu menetap. Menyatu dalam administrasi, menjadi kelurahan. Tapi di balik namanya yang resmi, ada nyawa-nyawa yang terbenam. Ada suara gamelan yang konon masih sesekali terdengar dari dasar sungai. Ada bayangan penari yang kabarnya melintas saat kabut turun.
Hari ini, mungkin tak banyak yang tahu. Tapi kisah ini tetap hidup. Di warung-warung kopi. Di beranda rumah tua. Dalam gumaman orang tua pada cucunya. Karena sejarah tak selalu tertulis di buku, tapi di hati warga yang terus mengingat.
Dan selagi Sungai Amprong terus mengalir, suara tandak itu, barangkali, masih menari di antara gelombang.(mit)