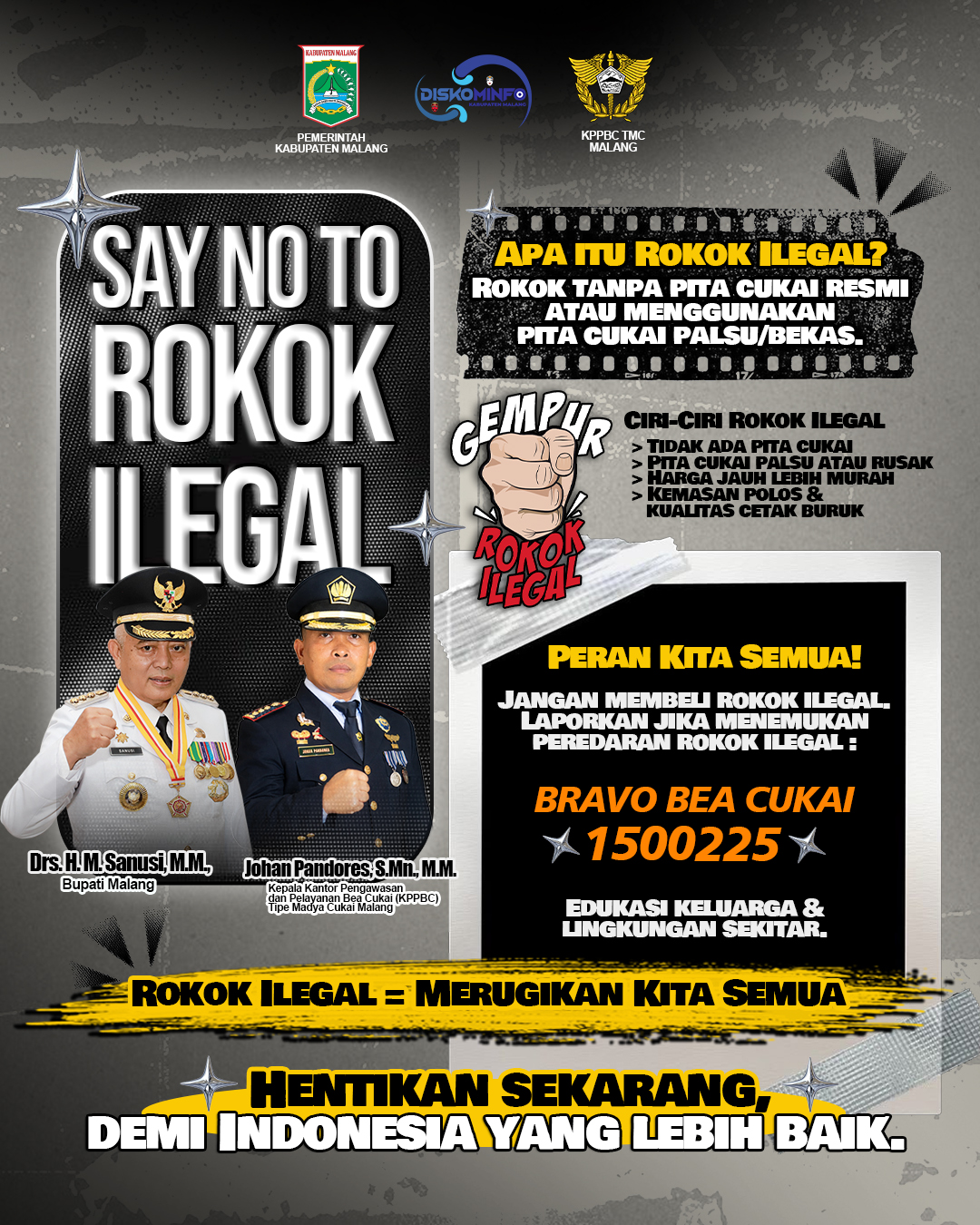Sudutkota.id – Kekosongan hukum terkait standar penilaian kerugian immaterial bagi korban kekerasan seksual anak kembali menjadi sorotan tajam. Ketidakjelasan regulasi dinilai menghambat upaya pemulihan psikologis korban, terutama dalam proses restitusi yang seharusnya menjadi hak hukum mereka.
“Ketidakpastian ini membuat pemulihan korban tidak pernah mencapai titik keadilan yang seharusnya,” ujar Taslim Pua Gading SH, MH, Jumat (28/11/2025).
Taslim menjelaskan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 memang mengatur hak korban atas restitusi materiil maupun immaterial. Namun, aturan tersebut belum merumuskan formula penghitungan nilai kerugian immaterial secara teknis.
“Secara normatif aturan sudah ada, tetapi tanpa pedoman penghitungannya, perlindungan itu nyaris tidak dapat dieksekusi secara optimal,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa ketiadaan standar nasional membuka celah multitafsir di tingkat aparat penegak hukum maupun di LPSK. Konsekuensinya, nilai restitusi yang diterima korban sangat berpotensi bergantung pada interpretasi subjektif masing-masing pihak.
“Ini situasi yang berbahaya karena mengalihkan fokus dari penderitaan korban ke sudut pandang penentu putusan,” kata Taslim.
Taslim kemudian mendorong pemerintah dan Mahkamah Agung segera membentuk formula baku bersama para ahli psikologi dan medis. Ia menegaskan bahwa tanpa standar tersebut, hak korban hanya akan menjadi formalitas administrasi semata.
“Jika formula nasional tidak disusun, korban tetap akan dipandang sebagai angka kasus, bukan manusia yang haknya wajib dipulihkan,” pungkasnya.
Senada dengan Taslim, Nico Yanuar Rahman menilai kaburnya standar restitusi immaterial justru menimbulkan ketidakadilan antar putusan.
Ia menyoroti putusan Mahkamah Agung No. 7346 K/Pid.Sus/2024 yang hanya menetapkan restitusi sebesar Rp4.610.000 bagi korban anak, meski trauma psikologisnya berkepanjangan.
“Angka itu jauh dari rasa keadilan yang semestinya diterima korban,” ujar Nico.
Nico juga mengkritik sejumlah putusan pengadilan negeri yang menentukan restitusi berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku, bukan tingkat kerugian mental korban.
Sebagai contoh, ia menyebut putusan PN Wonosari yang mengabulkan hanya Rp1.356.500 dari permohonan Rp9.156.500 meskipun korban mengalami trauma berat.
“Jika restitusi diukur dari kemampuan pelaku, penderitaan korban sama sekali kehilangan relevansinya,” tegas Nico.
Menurutnya, lemahnya regulasi turut diperparah oleh belum optimalnya pelaksanaan mekanisme pendanaan pemulihan korban melalui UU TPKS, sehingga pemenuhan hak restitusi masih bergantung pada kondisi finansial pelaku.
Kondisi tersebut membuat banyak kasus akhirnya diputus tanpa restitusi immaterial sama sekali.
“Ini membuktikan bahwa korban belum benar-benar ditempatkan sebagai pusat perhatian peradilan,” ungkap Nico.
Nico menegaskan bahwa pembentukan standar nasional restitusi immaterial merupakan urgensi mendesak untuk menciptakan keadilan restoratif yang sesungguhnya bagi korban anak.
Ia menilai pemulihan psikologis korban seharusnya dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara, bukan sekadar formalitas proses hukum.
“Negara wajib hadir penuh dalam memastikan pemulihan korban, karena amanat undang-undangnya jelas,” tutup Nico.